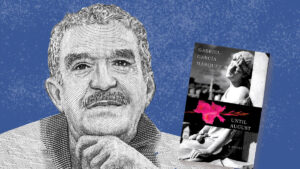Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram
Langgan SekarangHidayyah AT Mizi merenung dengan lebih mendalam tulisan Mana Sikana dalam kolum Sinar Ahad tentang sajak merapu dan lambakan puisi dalam media sosial.
Apabila seseorang penulis rajin menulis sajak di media sosialnya, dia bukanlah menulis kerana merasakan penulisan tersebut mudah, sebaliknya sebagai satu manifestasi tindakan dan pembelajaran kendiri yang diusahakan dalam usaha meningkatkan mutu karyanya. Sekiranya hal ini menimbulkan salah faham sehingga ditakrifkan seolah-olah menjadi punca kerosakan dan racun kesusasteraan, di gelanggang mana lagi penulis-penulis ini boleh berlatih untuk menajamkan kemahiran menulis mereka?
Istilah “sajak/puisi merapu” seharusnya digugurkan sebelum sesebuah wacana bersambut dan ditulis semula. Hal ini kerana, istilah tersebut membawa konotasi negatif dan memberi persepsi buruk secara mendalam terhadap usaha membangunkan dunia perpuisian negara.
Rasanya, sudah cukuplah sebilangan pihak berautoriti dan penulis mapan (kenyataan individu) mengherdik penulis-penulis pemula yang menulis di media sosial dengan mengatakan tulisan mereka merapu (dalam perbincangan ini, sajak/puisi).
Istilah “puisi merapu” tidak seharusnya dipolemikkan kerana perbincangan tentangnya bukanlah mengupas sesebuah karya per se, sebaliknya perbincangan lebih tertumpu kepada hal-hal luar karya.
Sejujurnya, kepada siapakah kritikan ini ditujukan? Apabila selesai membaca kritikan yang ditulis oleh Mana Sikana, kita seakan-akan dibawa ke alam labirin yang tunggang-langgang.
Apabila seseorang penulis rajin menulis sajak di media sosialnya, dia bukanlah menulis kerana merasakan penulisan tersebut mudah, sebaliknya sebagai satu manifestasi tindakan dan pembelajaran kendiri yang diusahakan dalam usaha meningkatkan mutu karyanya. Sekiranya hal ini menimbulkan salah faham sehingga ditakrifkan seolah-olah menjadi punca kerosakan dan racun kesusasteraan, di gelanggang mana lagi penulis-penulis ini boleh berlatih untuk menajamkan kemahiran menulis mereka?
Begitu ironikah dunia perpuisian di negara kita sehingga kesungguhan disalahertikan sedemikian rupa?
Suara kritikan Mana Sikana seolah-olah ayam berkokok di laut. Pertamanya, kerana konteks perbincangan sedari awal membina kepompong terhadap penulis di media sosial, sedangkan media sosial merupakan ruang peribadi. Perasaannya seperti sepasang suami isteri ditangkap berkhalwat di dalam hotel. Salahnya siapa dan apa kesalahannya? Bukankah sedari awal perbincangan bermula songsang?
Apabila Mana Sikana memilih untuk membahaskan lambakan karya kurang bermutu, seharusnya konteks perbincangan perlu dihalakan kepada kumpulan penulis yang karyanya sudah tersiar di media.
Soalan yang tepat untuk ditanyakan ialah, “Adakah penulis yang karyanya menembusi media, menulis karya yang bermutu?” Mengapa soalan ini penting? Hal ini kerana kritikan terhadap karya telah terbit lebih menghuraikan persoalan yang lebih serius, perbincangan yang lebih bersasar dan kemudiannya jika perlu, boleh juga disisipkan dengan teknik pengkaryaan yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan puisi yang lebih bermutu.
Namun begitu, hal sebaliknya yang terjadi. Mana Sikana sekadar memperkenalkan Teori Teksdealisme tanpa sebarang huraian atau penambahan ilmu bantu sebagai alat penulisan. Berbanding sekadar menjadikan Teksdealisme sebagai poin tempelan, Mana Sikana sepatutnya bersikap lebih terbuka dengan menunjukkan teknik menulis puisi yang lebih berkesan dengan pengaplikasian teori tersebut. Namun hal ini tidak terjadi. Sekadar membicarakan teori pada peringkat permukaan tidak akan membawa penulis pemula pada kefahaman yang diperlukan bagi merencanakan perjalanan peta penulisan mereka.
Keperluan teori perlu dibincangkan selaras penggunaannya, sesuailah dengan pengaplikasian dalam kerja-kerja penulisan. Dengan cara ini, penulis pemula akan berusaha untuk menulis dengan lebih baik. Malah, esei tentang pengaplikasian tersebut akan lebih mudah menjadi rujukan untuk tulisan-tulisan mereka yang seterusnya.
Sekurang-kurangnya, kritikan sebegini akan memberi nilai tambah kepada pemain industri dan pihak berautoriti yang berkepentingan untuk menyediakan jalan keluar terhadap isu utama, iaitu masalah lambakan penulisan puisi yang lemah dalam kalangan penulis semasa.
Teori sebagai alat bantu penulisan mungkin lebih bersifat sedikit mengongkong dan menjadi punca sakit kepala; tetapi sekiranya diterangkan dalam bentuk pengaplikasian yang lebih mudah cakna, hal ini akan dilihat sebagai satu lagi kaedah pemurnian penulisan. Kemudian, terpulang kepada para penulis untuk membuat penilaian kaedah pengkaryaan yang ingin diguna pakai.
Ketika kita sedang membina fenomena dalam dunia sastera, mengapakah isu-isu perlecehan masih terus diangkat sebagai wadah kritikan, padahal kritikan seharusnya berlaku demi menambahbaikkan nilai?
Hal kedua pula, wujudnya unsur perlecehan melampau dengan penggunaan istilah puisi “merapu”. Apakah yang merapu?
Persoalan ini membawa kepada persoalan yang lebih besar; apakah sebenarnya yang mahu dikritik? Siapakah yang tergolong dalam kumpulan penulis yang menulis puisi yang lemah? Apakah kriteria puisi lemah? Adakah hal ini berlaku kerana kelemahan mekanisme kesusasteraan negara sehingga terjadinya lambakan puisi yang lemah? Siapakah yang bertanggungjawab menggerakkan usaha memperkenalkan puisi yang baik kepada khalayaknya? Apakah tindakan yang telah dan sedang diambil? Apakah bentuk atau ilmu bantu terbaharu yang boleh digunakan oleh penulis sebagai jalan keluar pada permasalahan tersebut?
Ketika kita sedang membina fenomena dalam dunia sastera, mengapakah isu-isu perlecehan masih terus diangkat sebagai wadah kritikan, padahal kritikan seharusnya berlaku demi menambahbaikkan nilai?
Sedangkan, masih banyak isu yang penting belum lagi disentuh. Contohnya, isu tentang kebolehpasaran karya melawan nilai sastera. Bukankah hal ini lebih membimbangkan?
Dalam keadaan kebolehpasaran karya sastera yang sudah pun rendah; adakah kita masih perlu berpeluk tubuh dan asyik mengenangkan kehebatan perkembangan sastera terdahulu? Buku-buku sastera tidak selaris buku-buku lain. Apakah puncanya penyebab sastera gagal mendominasi minat khalayak untuk membelinya?
Daya tahan pasaran sudah berubah. Adakah penulis sekarang perlu berkembang mengikut acuan pemikiran dan gaya daripada kumpulan penulis terdahulu maka barulah diiktiraf perkembangan mereka? Bukankah penulis masa kini perlu dididik mengikut acuan dan norma hidup terkini, tanpa menidakkan keberadaan teknologi rangkaian media dan platform sosial?
Selain isu-isu enteng pasaran sastera, ruang latihan mempertajam kemahiran, dorongan dan motivasi merupakan antara elemen penting yang perlu dibincangkan dengan mendalam dan khusus, dalam menghidupkan kesusasteraan. Jika kesemua ini ditiadakan, bagaimanakah bakat seseorang penulis dapat dikembangkan?
Isu tentang lambakan puisi ini akhirnya dilihat sebagai upaya retorik yang dicetuskan kerana “marahkan nyamuk, kelambu terbakar”. Namun begitu, janganlah sampai isu ini ditunggang, sehingga kita sudah tidak tahu yang mana kepala dan yang mana ekornya.
Dan sepanjang menulis reaksi balas ini, terlalu banyak persoalan yang tidak berjawapan muncul di fikiran. Sebahagiannya diajukan dan sebahagian lagi tinggal berteka-teki dalam benak jiwa.
Ada sedikit terkilan di hati. Seolah-olah kritikan Mana Sikana tidak memasakkan konteks yang jelas sebelum gelanggang perbincangan dibuka. Entah bagaimana seharusnya “kita” menanggapi kritikan tanpa konteks jelas sebegini.
Entah bagaimanalah, ya?
Kredit Foto: Tamara Velazquez/Unsplash
_________________________
Hidayyah AT Mizi ialah penulis dari Perak. Beliau banyak menyumbangkan puisinya di beberapa media massa. Kata-kata yang Muncul di Cermin (Kata-Pilar, 2021) merupakan kumpulan puisi sulungnya.